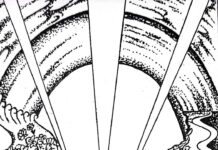IM.com – Pada peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember, Jawa Timur kembali mencatat jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi secara nasional. Data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jatim tahun 2025 menunjukkan sedikitnya 65.238 orang hidup dengan HIV/AIDS di provinsi ini.
Dalam kurun Januari–Maret saja, terdapat 2.599 kasus baru, menempatkan Jatim sebagai episentrum penyebaran HIV di Indonesia.
Data Kemenkes memperlihatkan lima wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, antara lain Kota Surabaya 368 kasus, Kabupaten Sidoarjo 270 kasus, Jember 229 kasus,
Tulungagung 209 kasus, sedangkan Kabupaten Pasuruan sebanyak 178 kasus.
Angka tersebut menunjukkan HIV tidak lagi terkonsentrasi pada kawasan tertentu, melainkan menyebar mengikuti mobilitas masyarakat dan perubahan pola perilaku berisiko.
Di tengah sorotan publik, jagat media sosial turut ramai oleh unggahan akun @data.kita yang menempatkan Kabupaten Sidoarjo dengan 270 kasus HIV, tertinggi kedua setelah Surabaya.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes mengatakan, bahwa data tersebut perlu dipahami secara proporsional.
Angka yang tinggi bukan berarti kasus HIV di Sidoarjo meningkat tajam, melainkan mencerminkan keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan skrining dan deteksi dini di berbagai lapisan masyarakat.
Namun, analisis lapangan menunjukkan bahwa tingginya angka HIV di Jawa Timur tidak berdiri sendiri. Ada faktor sosial, perubahan pola prostitusi, dan minimnya edukasi reproduksi yang memperluas risiko penularan.
Lokalisasi Ditutup
Pengawasan Hilang
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur menutup lokalisasi dan mengklaimnya sebagai kemenangan moral. Namun penutupan itu justru memunculkan persoalan baru dalam pengawasan kesehatan masyarakat.
“Sebelum lokalisasi ditutup, petugas kesehatan bisa memeriksa para pekerja seks secara teratur. Setelah mereka menyebar, pemeriksaan itu hampir tak mungkin dilakukan,” ujar Farid Hafifi, Direktur Yayasan Mahameru, lembaga yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi remaja di Surabaya, (1/12/2025).
Menurut Farid, penutupan lokalisasi menghilangkan titik pemetaan yang selama ini menjadi pintu masuk edukasi, distribusi kondom, dan tes kesehatan berkala.
“Sekarang jaringan prostitusi berpindah ke ruang-ruang yang tidak kasat mata. Risiko meningkat karena akses kesehatan justru makin jauh,” tambahnya.
Digitalisasi Prostitusi
Sejumlah penggiat kesehatan masyarakat menyebut adanya tranformasi prostitusi jadi beberapa pola yang sulit diawasi.
Seperti Prostitusi motor (mobile sex work). Transaksi dilakukan melalui telepon dan media sosial. Pekerja seks bergerak cepat menggunakan motor, tanpa lokasi tetap. “Tidak ada titik yang bisa dipetakan. Jejak digital pun mudah dihapus,” kata Farid.
Migrasi ke hotel-hotel kecil. Pemerintah sering memamerkan kawasan yang bersih dari lokalisasi, namun hotel-hotel kecil justru ramai aktivitas short time yang tertutup dari regulasi.
Prostitusi berbasis aplikasi. Menggunakan layanan pesan terenkripsi, kode internal, atau platform kencan. “Ini dunia baru yang tidak bisa ditembus petugas lapangan. Sangat sulit dijangkau program kesehatan,” ujar Farid Hafifi.
Transformasi ini menjadikan struktur pelacuran semakin cair, berbasis jaringan kecil, tanpa sentra, dan cenderung lebih berisiko karena kehilangan akses kesehatan preventif.
Kondisi serupa disampaikan Naim, penyembuh alternatif di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo, yang sering menerima pasien perempuan muda positif HIV.
“Kebanyakan dari mereka cewek-cewek Sidoarjo yang bekerja sebagai penghibur di diskotik Surabaya. Banyak pula pelanggan dari daerah petambak seperti Sidoarjo, Lamongan, dan Gresik,” tuturnya.
Pola mobilitas tinggi antara Sidoarjo dan Surabaya menjadikan risiko penularan lebih sulit dikendalikan. “Mereka sering datang setelah merasa sakit,” kata Naim.
Selain prostitusi digital, kelompok remaja juga menjadi perhatian serius. Surabaya mencatat banyak kasus HIV baru berasal dari kelompok usia muda.
Menurut Farid Hafifi dari Yayasan Mahameru, 20–30 persen remaja dampingan mereka tidak pernah menerima edukasi kesehatan reproduksi secara memadai.
“Banyak anak SMA yang bahkan tidak tau cara penularan HIV. Mereka belajar dari media sosial, padahal banyak informasi yang menyesatkan,” ujarnya.
Farid menegaskan perlunya pembaruan kurikulum di sekolah. “IPA, Biologi, dan BK seharusnya jadi ruang aman untuk membahas relasi, batasan, seks yang aman, dan risiko kesehatan. Tidak boleh lagi dianggap tabu,” katanya.
Para ahli kesehatan menekankan bahwa penanganan HIV tidak bisa hanya berupa penutupan lokalisasi atau kampanye moral.
“Kebijakan yang tidak berbasis kesehatan publik justru membuka ruang gelap penularan,” tegas Farid Hafifi.
Diperlukan langkah-langkah strategis dengan memberikan edukasi reproduksi komprehensif. Skrining rutin di lokasi-lokasi berisiko serta layanan kesehatan ramah pekerja seks dan remaja. Juga mengikuti perubahan model prostitusi digital.
Tanpa itu semua, Jawa Timur akan terus menjadi provinsi dengan angka HIV tertinggi. Bukan karena masyarakat kurang bermoral tapi karena kebijakan kesehatan tidak mengikuti perubahan zaman. (kim/wid)