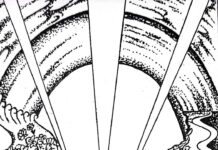IM.com – Taman Budaya Jawa Timur kembali menyiratkan gairah kreativitas kesenian tradisi ketika Parade Jaranan 2025 digelar selama dua malam, Kamis–Jumat, 27–28 November 2025.
Bertempat di Pendhapa Taman Budaya dan Gedung Kesenian Cak Durasim, jalan Gentengkali Surabaya. Gelaran ini menampilkan sepuluh komunitas dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Banyuwangi, hingga Surabaya.
Sebanyak 400 kursi dipenuhi penonton sebagai bukti bahwa kesenian jaranan memiliki daya pikat untuk diapresiasi.
Tidak sekadar pertunjukan, Parade Jaranan tahun ini menghadirkan tafsir-tafsir baru dari para sutradara yang menempatkan jaranan sebagai medium reflektif, spiritual, sekaligus ruang dialog kreatif antara tradisi dan gagasan kontemporer.

Menghidupkan Mitos
Kelompok jaranan Sardulo Jaya Djojo dari Malang yang disutradarai Ropik Saputra menyajikan tema Lebyaning Sato Reridhu.
Ropik Saputra membawa penonton ke dalam kisah kadipaten Kutho Bedhah yang diguncang hama perusak hasil bumi. Melalui gerak prajurit dan karakter hewani, ia menuturkan konflik klasik antara kemakmuran dan ancaman yang mengintainya.
“Saya ingin mengingatkan bahwa kemakmuran selalu mengundang ujian. Jaranan bukan sekadar tontonan, tapi medium untuk menyampaikan nilai kewaspadaan dan keberanian,” kata Ropik.
Didukung penata artistik Paulina Merry Sugiharti, musik Samuel Bayu, serta tata rias Shaslsabilla Eka, pertunjukan ini tampil sebagai dramatika heroik yang kaya warna.
Turonggo Djati dari Kediri mengusung lakon Tayungan dengan sutradara Didik Pranotomenyuguhkan renungan filosofis tentang perjalanan hidup manusia. Dalam tafsirnya, jaranan menjadi jejak spiritual yang menimbang baik–buruk, rintangan dan ikhtiar.
“Kehidupan tidak lepas dari pilihan moral. Yang mistis dalam jaranan sebenarnya adalah cermin dari pola pikir dan kebiasaan manusia sendiri,” ujar Didik. Gerak yang ritmis dan tegas menjadi kekuatan naratif pertunjukan Tayungan.
Dari Surabaya diwakili Aulio Utomo menyajikan repertoar Jurit Panegar olahan sutradara Caroko Paku Wijaya menggambarkan ekosistem gagasan berupa tradisi, klasik dan kontemporer dijalin menjadi satu kesatuan.
“Kami tidak sekadar ingin tampil, tapi belajar memahami dan mencintai kebudayaan kita. Proses kreatif harus melahirkan pribadi yang tumbuh, bukan hanya karya yang megah,” ujar Caroko.
Dengan komposisi musik Nopan Dwi Ramadhan, karya ini tampil energik dan menjunjung semangat kolaboratif.
Baya Runcing dari Surabaya menampilkan Turonggo Yasko, disutradarai Danu Sholeh Cahyono, menggarap pergulatan batin manusia melalui drama kesatria dan celeng, simbol nafsu yang mudah menggoyahkan keutamaan moral.
“Musuh terbesar manusia bukan di luar dirinya, tetapi apa yang tumbuh di hati. Jaranan memberi cara artistik untuk merenungkan itu,” tuturnya.
Gerak ritmis, permainan karakter, serta estetika artistik Irfan Nur Muhammad menjadi kekuatan utama karya ini.
Sementara kelompok Lestari Widodo Wiryotama dari Tulungagung menyajikan Jaran Sentherewe dengan sutradara Hapsari Mustikaningrum. Repertoat ini berpijak pada tradisi Sentherewe yang menuturkan perjalanan hidup prajurit berkuda yang menaklukkan celeng dan barongan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kehidupan penuh marabahaya tetapi manusia selalu punya daya untuk bangkit. Tradisi Sentherewe memberi bahasa gerak yang kuat untuk itu,” jelas Hapsari. Motif kebaruan dipadukan dengan ragam klasik tanpa kehilangan akar tradisinya.
Parade dua malam ini mencerminkan keberagaman tafsir dan kekayaan estetika jaranan Nusantara. Para sutradara tidak hanya menampilkan karya, tetapi juga menyampaikan pesan moral, spiritual, dan sosial melalui bahasa gerak yang hidup.
Melihat antusiasme penonton dan keberanian para koreografer memperlihatkan bahwa jaranan tetap relevan sebagai hiburan yang menyenangkan. (kim)